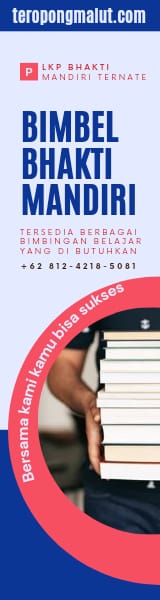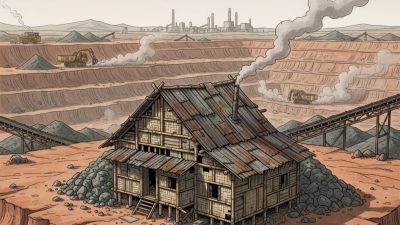Oleh: Yati Suharyati
Ternate-TeropongMalut.com, Hilirisasi komoditas kelapa di Maluku Utara belakangan menjadi topik hangat dalam diskursus pembangunan daerah. Program ini digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di balik narasi “kemajuan ekonomi”, terdapat persoalan serius yang perlu dikritisi secara objektif, terutama ketika proyek ini menggandeng investor asing — termasuk dari Tiongkok (China) — yang justru berpotensi menjadi pihak paling diuntungkan.
Tindak lanjut dari kebijakan hilirisasi kelapa, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, telah bekerjasama dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan area tanah tidur. Ini sebagai salah satu upaya strategis dalam mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa. Gubernur juga telah meluncurkan 12.000 lowongan kerja bagi pemanjat kelapa melalui aplikasi Job Seeker untuk mendukung tenaga kerja dalam kebijakan hilirisasi kelapa.
Bergantung Investor
Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Sayangnya, selama ini masyarakat hanya berada di level hulu — menjual kelapa mentah tanpa pengolahan. Hilirisasi sejatinya dimaksudkan untuk mengubah pola ini, agar masyarakat tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga turut menikmati nilai tambah dari hasil olahan seperti minyak kelapa murni, sabun, atau produk turunan lainnya.
Namun, dalam praktiknya, proyek hilirisasi ini justru lebih dikendalikan oleh investor. Saat ini olahan kelapa di produksi oleh investor lokal PT NICO di Halut. Kedepan rencananya akan berkolaborasi dengan investor China. Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Maluku Utara telah menjalin kemitraan strategis bersama Pemerintah China guna mengembangkan kawasan transmigrasi terpadu di Indonesia bagian timur. Akhir tahun ini akan datang investor China ke Halmahera Utara untuk melihat langsung potensi kelapa.
Investor selama ini, terutama investor asing mendapatkan izin investasi dengan skema kerja sama yang minim transfer teknologi. Artinya keuntungan hilirisasi akan masuk ke kantong investor, karena teknologi yang dipakai milik mereka. Indonesia sejauh ini tidak memiliki smelter sendiri. Karena sistem perbankan yang tidak memberikan pendanaan bagi para pengusaha. Sedangkan Tiongkok mampu membangun sendiri industrinya karena mereka membeli dan mentransfer teknologinya.
Penguasa Kapitalisme
Kondisi demikian muncul karena negara tidak berperan sebagai pe-riayah (pengurus) kebutuhan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator atau fasilitator, sekadar membuat UU untuk memudahkan para oligarki menguasai SDA negeri. Jadi, setinggi apa pun cita-cita pemimpin negeri ini atau sebaik apa pun kebijakan yang dibuat, tidak akan mengangkat harkat dan derajat bangsa di dunia Internasional.
Ketergantungan pada investor asing dapat menimbulkan bentuk baru dari kolonialisme. Di mana daerah kaya sumber daya justru tidak berdaulat atas hasil buminya sendiri, justru dikelola asing. Dalam jangka panjang, pola ini hanya memindahkan ketimpangan dari pusat ke daerah.
Hilirisasi, walaupun tetap ada yang didapat seperti terciptanya lapangan kerja, tapi hanya sebatas sebagai tukang jahit. Sedangkan keuntungan nilai tambah (coconut milk, minyak kelapa murni (VCO), dan berbagai turunan lainnya) dari hilirisasi masuk ke kantong investor. Apakah pemerintah tidak berkaca pada hilirisasi nikel? Penikmat hilirisasi nikel adalah China. keuntungan China terlihat dari mengalirnya 80-90% ekspor barang setengah jadi ke China. Jadi penikmati utamanya adalah pelaku industri yang ada di China, perusahan-persahaan China. Sama seperti hilirisasi kelapa ini. Ekspor kelapa Indonesia ke Cina beberapa bulan meningkat karena permintaan tinggi dari industri olahan, khususnya susu kelapa.
Solusi dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif industri pangan, Islam tidak membiarkan sektor-sektor strategis—seperti kelapa—dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta. Negara justru hadir secara serius dengan memberikan standar riset yang jelas, dukungan permodalan, teknologi pengolahan yang memadai, hingga fasilitas promosi. Seluruh kebutuhan tersebut ditopang oleh negara, sehingga produk pangan mampu bersaing di pasar internasional.
Namun, sebelum berbicara tentang ekspor, Islam menekankan kewajiban utama seorang pemimpin: memastikan seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan. Negara harus memastikan warganya makan dengan layak, cukup, dan bergizi sebelum mengalihkan perhatian ke pasar luar negeri.
Hilirisasi memang memerlukan modal yang besar. Dalam sistem Islam, modal tersebut diperoleh melalui Baitulmal, yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam, jizyah, ganimah, fai’, kharaj, dan pos-pos pemasukan lainnya. Dengan demikian, umat tidak perlu bergantung pada investor asing atau pihak swasta besar. Dukungan negara inilah yang memungkinkan komoditas pangan—termasuk sektor peternakan—mampu bersaing di tingkat global. Keuntungan yang diperoleh pun kembali kepada masyarakat, sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.
Hilirisasi kelapa di Maluku Utara sejatinya adalah peluang besar untuk peryumbuhan ekonomi daerah. Namun, jika dijalankan dengan pola kapitalistik dan ketergantungan terhadap asing, maka rakyat hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
Sudah saatnya arah pembangunan ekonomi dikembalikan pada prinsip kedaulatan sebagaimana diajarkan Islam. Di mana sumber daya dikelola untuk kemaslahatan seluruh umat, bukan segelintir pihak yang memiliki modal besar. (Selesai)